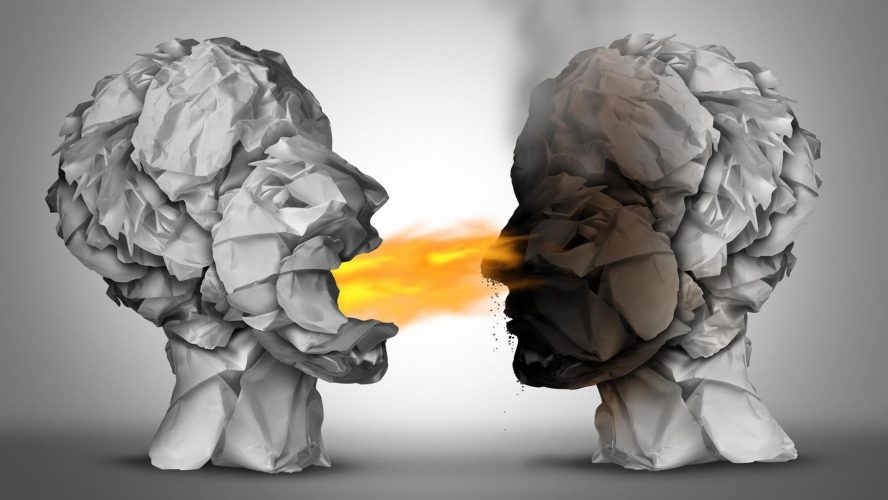
Ketika Netizen Membungkus Cancel Culture dengan Dalil Agama!
Fenomena cancel culture atau budaya pembatalan kini bukan lagi hal asing di dunia maya. Istilah ini merujuk pada aksi kolektif masyarakat, terutama di media sosial, untuk “menghukum” tokoh publik, selebritas, atau siapa pun yang dianggap melakukan kesalahan, baik secara etika, sosial, maupun moral. Namun yang menjadi perhatian serius adalah ketika praktik cancel culture ini dibungkus dengan dalil-dalil agama.
Belakangan, banyak netizen yang tidak sekadar mengecam seseorang karena kesalahannya, tetapi juga melabeli dengan sebutan-sebutan keagamaan seperti “kafir”, “sesat”, atau “murtad”. Bahkan dalam beberapa kasus, ada yang memaksakan iam-love.co pemboikotan atau pengasingan sosial terhadap seseorang dengan mengutip ayat suci atau hadis, seolah menjadi pembenaran mutlak atas tindakan mereka. Kondisi ini memunculkan pertanyaan penting: apakah benar membatalkan atau menghakimi seseorang di media sosial dengan dalih agama adalah tindakan yang tepat?
Secara esensial, ajaran agama, terutama Islam sebagai agama yang paling sering dikaitkan dalam konteks ini di Indonesia, sangat menjunjung tinggi adab, tabayyun (klarifikasi), serta prinsip kasih sayang. Ketika seseorang bersalah, agama tidak mengajarkan untuk langsung menghakimi tanpa proses klarifikasi. Dalam Islam misalnya, terdapat kaidah bahwa seseorang tidak boleh dihukumi sebelum mendengar penjelasan dan bukti yang sahih. Akan tetapi, netizen sering kali mengambil jalan pintas dengan langsung menyebar kutipan agama tanpa melihat konteksnya secara utuh.
Tindakan ini dapat menimbulkan dua masalah besar. Pertama, penggunaan dalil agama secara sembarangan bisa menyebabkan salah paham terhadap ajaran agama itu sendiri. Orang awam yang membaca komentar tersebut bisa mengira bahwa Islam mendorong untuk memutus silaturahmi atau menghina orang lain jika melakukan kesalahan. Kedua, ini bisa menjadi bentuk kezaliman digital yang berujung pada kekerasan psikologis bagi pihak yang diserang.
Perlu disadari, cancel culture sering kali bergerak berdasarkan emosi dan asumsi, bukan atas prinsip keadilan yang objektif. Ketika agama digunakan sebagai alat untuk membenarkan cancel culture, yang terjadi justru pembalikan nilai: agama yang sejatinya membawa rahmat dan pencerahan, malah dipakai untuk menjustifikasi pengucilan dan penghukuman sosial.
Sebaliknya, agama mengajarkan pentingnya memberi kesempatan kepada seseorang untuk berubah, memperbaiki diri, dan bertaubat. Dalam banyak kisah tokoh-tokoh spiritual, bahkan orang yang pernah berdosa besar tetap diberikan pintu maaf dan ruang untuk memperbaiki hidupnya. Jika media sosial hari ini justru menutup pintu itu, maka kita patut bertanya: di mana letak nilai spiritualitasnya?
Menyoroti fenomena ini bukan berarti membenarkan kesalahan yang dilakukan oleh publik figur atau tokoh tertentu. Kritik dan pengingat memang diperlukan. Namun, akan lebih bijak bila dilakukan dengan cara yang beradab, penuh empati, dan jauh dari semangat menghakimi. Cancel culture yang dibungkus dalil agama justru bisa menodai pesan agama itu sendiri, menjadikannya alat kekuasaan massa alih-alih sebagai sumber kasih dan kebaikan.
Pada akhirnya, media sosial memang memberi kekuatan pada publik, namun kekuatan itu perlu disertai dengan tanggung jawab moral. Kritik boleh, tapi menghakimi tanpa belas kasih bukanlah ajaran agama mana pun.
BACA JUGA: Dosen UK Petra Surabaya Tanggapi Budaya Cancel Culture: Ajakan untuk Edukasi dan Empati

Dosen UK Petra Surabaya Tanggapi Budaya Cancel Culture: Ajakan untuk Edukasi dan Empati
Fenomena cancel culture atau budaya pembatalan kini menjadi perbincangan hangat, terutama di era media sosial yang berkembang pesat. Budaya ini merujuk pada tindakan kolektif masyarakat untuk memboikot atau mengkritik keras seseorang, biasanya figur publik, akibat pernyataan atau tindakan yang dianggap tidak pantas. Meski pada dasarnya lahir dari dorongan moral, praktik cancel culture dinilai menyimpan banyak dilema etis. Menanggapi isu ini, salah satu dosen Universitas Kristen Petra (UK Petra) Surabaya, Meilinda, S.S., M.A., memberikan pandangan kritisnya.
Meilinda, yang merupakan dosen Program Studi English for Creative Industry UK Petra, melihat bahwa cancel culture memiliki dua sisi yang perlu dipahami secara mendalam. Di satu sisi, budaya ini bisa menjadi sarana bagi masyarakat untuk menuntut tanggung jawab dari pihak yang melakukan kesalahan. Namun di sisi lain, ia menilai bahwa pembatalan yang dilakukan secara terburu-buru, tanpa pemahaman konteks atau fakta lengkap, justru bisa menimbulkan kerugian yang lebih luas.
“Sering kali masyarakat terlalu cepat bereaksi. Tanpa mendalami konteks, seseorang bisa langsung dihakimi dan dijatuhkan reputasinya. Ini tentu bisa membahayakan,” jelas Meilinda.
Menurutnya, yang menjadi korban dalam budaya pembatalan tidak hanya individu yang disorot, melainkan juga pihak-pihak lain yang terkait. Ia memberi contoh pada kasus selebritas atau publik figur yang dibatalkan akibat satu kesalahan; seluruh tim di balik layar—mulai dari penulis, kru produksi, hingga staf pemasaran—ikut merasakan dampaknya. Kontrak kerja bisa dibatalkan, proyek dihentikan, dan reputasi profesional ikut tercoreng.
Lebih lanjut, Meilinda mengajak masyarakat untuk lebih mengedepankan empati dan pendekatan edukatif ketimbang sanksi sosial. Ia menilai bahwa alih-alih langsung “membatalkan” seseorang, masyarakat dapat mengedepankan dialog, kritik yang membangun, dan memberi ruang bagi individu tersebut untuk belajar dan memperbaiki diri.
“Kalau kita ingin perubahan yang sejati, kita harus membangun budaya komunikasi yang sehat. Edukasi jauh lebih berdampak daripada hanya menghukum,” ujarnya.
Media sosial menjadi medium daftar rajazeus utama dalam berkembangnya cancel culture. Meilinda menyoroti bahwa kecepatan dan kebebasan berbicara di platform digital memang menjadi kekuatan, namun juga bisa menjadi bumerang jika tidak digunakan secara bijak. Ia menegaskan pentingnya literasi digital, khususnya untuk generasi muda, agar dapat memilah informasi dan tidak terjebak dalam arus penghakiman massal.
Sebagai penutup, Meilinda mengingatkan bahwa dalam masyarakat yang beradab, proses perbaikan dan pertumbuhan pribadi harus diberi ruang. Tidak semua kesalahan harus dibayar dengan “penghilangan” seseorang dari ruang publik. Dengan pendidikan, empati, dan kepekaan sosial yang tinggi, masyarakat dapat membentuk budaya yang lebih sehat dan konstruktif.
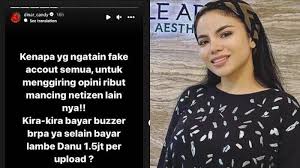
5 Artis Hobi Membalas Komentar Nyinyir Netizen
Sebanyak tujuh artis hobi membalas komentar nyinyir dari netizen. Mereka tak tka takut dan membalas segala komentar pahit netizen usil. Artis kini telah banyak bersikap tak ingin netizen semena-mena seakan paling benar.
Berikut tujuh artis hobi membalas komentar nyinyir dari netizen.
1. Nindy Ayunda
Nindy Ayunda sering membalas komentar nyinyir netizen. Maudy tampak slot joker tak ingin netizen bersikap kasar dan nyinyir merasa paling benar.
“Jatuh nya mba nindy kayak pakai piama gt ya. apa akunya yg kurang tau tren,” kata akun @junesw26.
“Hadeuhhh ko bajunya kaya gitu ya gk cuco banget,,emang gk ngaca dulu gitu ya. btw emang cantik sih,” tulis akun @rossekar.
Nindy Ayunda sempat mendapatkan komentar ketika mengenakan piyama. Tak ingin terus dinyinyiri netizen, Nindy langsung berkomentar di akun Instagram miliknya.
“Ya Allah, ini upil naruto masih pada berisik aja komenin piyama gue,” tulis Nindy.
2. Rina Nose
Usai melepas hijab, Rina Nose kerap mendapatkan komentar pedas dari netizen. Penampilan terbuka tak luput dari perhatian netizen. Pernah dada Rina Nose mendapatkan komentar pedas dari netizen.
“Sudah hampir nampak belahan yang dulu ditutupin hijab tuh, dunia yang aneh, ada apa ini?,” tulis netizen.
Menanggapi hal tersebut, Rina pun membalas komentar salah satu netizen yang membawa-bawa agama dalam setiap penampilan mantan tunangan Fakhrul Razi tersebut.
“Nah, situ kenapa fokus kesitu? Mungkin otakmu yang perlu hijrah mas, bukan dunia yang aneh tapi otakmu itu,” tanggap Rina.
3. Bunga Zainal
Bunga Zainal juga sering mendapatkan komentar pedas dari netizen. Penampilan dan kisah rumah tangga sering kali jadi perhatian netizen.
Netizen pernah menyinggung Bunga Zainal sebagai perempuan matre. Bunga Zainal matre lantaran rela pindah agama demi menikah dengan produser ternama yang memiliki jarak usia 18 tahun dengannya. Menanggapi hal itu, Bunga pun membuat video menohok yang diunggahnya ke akun TikTok-nya, @bunga23zainal.
“Ketika temanmu kasih tahu kalau netizen gak percaya kamu nikah bukan karena harta,” tulis Bunga dikutip dari akun TikToknya.
4. Melly Goeslaw
Melly Goeslaw sempat geram ketika netizen mengomentari make up Laudya Cynthia Bella. Melly langsung menyemprot netizen.
“Punten sy kasih komen soal make up. Nikah itu ibadah, bukan dinilai dari tipis tebalnya sebuah make up, mahal murahnya baju pengantin, enak enggaknya cateringnya. Yg penting ijab, janji pada Allah. Aneh deh yang pada komen make up jiga nu gareulis waaaeeee,” tulis Melly.
5. Ariel Tatum
Ariel Tatum kerap tampil apa adanya. Namun demikian sikap Ariel banyak mengundang aksi tak pantas netizen. Ia kerap disindir netizen.
“Dasar p****r muka buled moga sekarat beneran lo kalau mampus di lingges truck. selangkangan bosok dimakan belatung,” tulis sebuah akun bernama @liyanaalfrina.
Ariel kemudian menjawab dengan santai. “@mayaramonasari astagfirullah.. sending you my love ang positivities mbak.. Saya doain semoga Tuhan selalu melindungi dirimu aamiin,” tulis Ariel.
Baca Juga : Cancel Culture 2025: Ketika Netizen Jadi Hakim di Dunia Maya Indonesia

Cancel Culture 2025: Ketika Netizen Jadi Hakim di Dunia Maya Indonesia
Fenomena cancel culture atau budaya pembatalan terus berkembang di Indonesia dan mencapai puncaknya pada tahun 2025. Muncul sebagai bentuk protes terhadap perilaku bermasalah dari figur publik, selebriti, maupun tokoh politik, cancel culture kini berkembang menjadi alat yang tajam sekaligus kontroversial di tangan warganet. Dalam banyak kasus, netizen Indonesia bahkan dianggap telah menjadi “hakim” digital yang menentukan siapa layak dihargai dan siapa yang harus dikucilkan.
Namun apakah ini bentuk kesadaran kolektif yang sehat? Ataukah justru menjadi praktik persekusi massal yang merugikan?
Apa Itu Cancel Culture?
Cancel culture adalah praktik sosial di mana seseorang atau kelompok dihentikan dukungannya secara publik—sering kali melalui media sosial—karena tindakan, pernyataan, atau pandangan yang dianggap ofensif, kontroversial, atau tidak sesuai dengan nilai moral masyarakat. Bentuknya bisa berupa:
-
Ajakan untuk unfollow di media sosial
-
Seruan boikot produk atau karya
-
Penyebaran tagar seperti #Cancel[namatarget]
-
Penggalian kesalahan masa lalu (digital digging)
Tren Cancel Culture di Indonesia Tahun 2025
Tahun 2025 menyaksikan lonjakan kasus cancel culture di Indonesia. Penyebabnya beragam—mulai dari isu moral, politik, agama, hingga kesalahan kecil di masa lalu. Beberapa tren mencolok meliputi:
1. Semakin Cepat, Semakin Viral
Dalam hitungan jam, sebuah video atau pernyataan bisa viral dan langsung memicu gelombang kemarahan warganet. Belum sempat klarifikasi dilakukan, target cancel sudah dihujat habis-habisan.
2. Target yang Semakin Luas
Dulu hanya selebriti dan tokoh publik yang jadi sasaran. Kini, influencer mikro, content creator kecil, bahkan individu biasa bisa tiba-tiba jadi “musuh bersama” karena sebuah postingan viral.
3. Tajam di Dunia Hiburan dan Politik
Figur publik yang tersandung isu rasisme, seksisme, body shaming, LGBT, atau politik identitas rentan jadi target. Bahkan salah mengucap satu kata sensitif saja bisa langsung memicu gelombang pembatalan.
Kekuatan dan Bahaya Cancel Culture
Cancel culture kerap dipandang sebagai bentuk akuntabilitas sosial. Ketika sistem hukum lamban atau tidak mampu memberikan keadilan, netizen mengambil peran sebagai “penegak moral”.
Contoh positif:
Kasus-kasus pelecehan seksual yang terangkat karena korban bersuara di media sosial dan mendapat dukungan publik. Dalam beberapa kasus, cancel culture mendorong investigasi dan tindakan nyata dari pihak berwenang.
Namun, cancel culture juga punya sisi gelap:
1. Tanpa Proses dan Klarifikasi
Seseorang bisa langsung dihakimi sebelum sempat memberikan penjelasan. Praduga tak bersalah kerap diabaikan.
2. Efek Jangka Panjang
Korban pembatalan bisa kehilangan pekerjaan, mengalami gangguan mental, atau bahkan dikucilkan sosial secara permanen. Dalam kasus ekstrem, ada yang sampai bunuh diri karena tekanan publik.
3. Salah Sasaran
Kadang orang yang tidak bersalah ikut terseret. Salah satu contohnya adalah kasus salah identitas—netizen memburu akun atau orang yang ternyata bukan pelaku sebenarnya.
Siapa Saja yang Bisa Kena Cancel?
Tak ada yang kebal. Berikut profil umum target cancel culture di Indonesia 2025:
-
Artis dan musisi: karena ucapan kontroversial, gaya hidup, atau sikap politis
-
Influencer media sosial: karena dianggap toxic, menyebarkan hoaks, atau bersikap tidak sensitif
-
Politikus dan pejabat publik: karena korupsi, pelanggaran etika, atau rekam jejak buruk
-
Merek dagang atau brand: karena bekerja sama dengan figur yang dibatalkan atau karena isu CSR
Netizen: Kekuatan Rakyat atau Teror Publik?
Di satu sisi, cancel culture membuktikan rajazeus link alternatif kekuatan kolektif masyarakat digital. Tapi ketika amarah lebih dominan daripada logika, hasilnya adalah penghakiman massa. Fenomena ini memunculkan pertanyaan besar:
-
Apakah semua orang layak mendapat kesempatan untuk berubah?
-
Siapa yang berhak memutuskan bahwa seseorang harus dikucilkan selamanya?
-
Apakah kita hanya ikut tren membatalkan tanpa berpikir kritis?
Menuju Budaya Kritik yang Lebih Dewasa
Cancel culture bisa menjadi kekuatan untuk kebaikan—jika digunakan dengan bijak. Namun untuk itu, kita perlu membangun budaya kritik yang sehat:
-
Pisahkan antara kritik dan hujatan
-
Berikan ruang klarifikasi sebelum membentuk opini publik
-
Fokus pada edukasi, bukan hanya penghakiman
-
Gunakan media sosial dengan empati dan tanggung jawab
-
Pahami konteks dan fakta sebelum menyebarkan sesuatu
BACA JUGA: Membatalkan di Era Global: Cancel Culture dalam Perspektif Budaya Dunia

Membatalkan di Era Global: Cancel Culture dalam Perspektif Budaya Dunia
Di era digital yang serba cepat, satu kesalahan di internet bisa membawa konsekuensi besar. Kata-kata, tindakan, atau bahkan pernyataan di masa lalu bisa diangkat kembali dan menjadi pemicu bagi publik untuk “membatalkan” seseorang atau suatu entitas. Fenomena ini dikenal luas sebagai Cancel Culture.
Istilah ini telah menjadi bagian penting dari percakapan global — baik di dunia hiburan, politik, hingga bisnis — dan menimbulkan perdebatan besar: apakah cancel culture merupakan bentuk keadilan sosial atau justru penghakiman massa digital yang tak adil?
Artikel ini mengulas cancel culture dari sudut pandang global, bagaimana setiap budaya menyikapinya, serta dampaknya terhadap masyarakat dan individu.
Apa Itu Cancel Culture?
Cancel culture slot spaceman merujuk pada praktik kolektif masyarakat — khususnya di media sosial — untuk memboikot, menarik dukungan, atau membungkam seseorang atau organisasi karena dianggap telah melakukan hal yang salah, tidak pantas, atau ofensif secara moral maupun sosial.
Contohnya bisa beragam: dari selebritas yang membuat komentar rasis, perusahaan yang tidak mendukung hak-hak minoritas, hingga politikus yang terlibat skandal.
Di satu sisi, cancel culture dianggap sebagai alat kontrol sosial dan bentuk akuntabilitas. Namun di sisi lain, ini juga bisa menjadi bentuk pembungkaman, terutama ketika dilakukan tanpa fakta utuh atau ruang untuk perbaikan.
Cancel Culture dalam Konteks Global
1. Amerika Serikat: Lahirnya Istilah “Cancel Culture”
AS adalah tempat di mana istilah ini pertama kali populer, khususnya melalui Twitter. Budaya bebas berpendapat yang kuat, dikombinasikan dengan masyarakat yang sangat terpolarisasi secara politik, membuat cancel culture berkembang pesat. Selebriti, CEO, hingga profesor universitas bisa “dibatalkan” dalam semalam karena kontroversi yang viral.
Contoh: J.K. Rowling dikritik keras karena komentarnya soal transgender, hingga menyebabkan banyak penggemar “membatalkan” dirinya meskipun karya Harry Potter tetap populer.
2. Korea Selatan: Budaya Perfeksionisme dan Pengaruh Netizen
Di Korea Selatan, cancel culture muncul dalam bentuk yang sangat kuat, terutama terhadap idol K-pop dan aktor. Karena budaya kerja keras dan ekspektasi tinggi, kesalahan sekecil apa pun bisa berujung pada permintaan maaf publik atau bahkan penghentian karier.
Contoh: Banyak artis yang kariernya tamat karena komentar masa lalu, dugaan bullying, atau perbuatan yang dianggap tidak sopan oleh publik.
3. Jepang: Budaya Malu dan Diamnya Pembatalan
Di Jepang, pembatalan terjadi lebih halus dan pasif. Masyarakat jarang menyerang langsung, tetapi mengekspresikan ketidaksetujuan melalui pengabaian sosial atau “pembekuan” dari komunitas. Individu atau tokoh publik bisa kehilangan pekerjaan, peran TV, atau kontrak tanpa banyak penjelasan publik.
4. Eropa: Campuran Toleransi dan Kritik Terbuka
Di Eropa, cancel culture memiliki karakter yang beragam tergantung negara. Di Inggris dan Prancis, misalnya, debat seputar kebebasan berpendapat vs tanggung jawab sosial menjadi inti. Banyak tokoh yang dibatalkan namun juga didukung oleh kelompok yang membela kebebasan berekspresi.
5. Indonesia: Cancel Culture yang Muncul Bersama Netizen +62
Cancel culture di Indonesia semakin terasa seiring meningkatnya pengguna media sosial. Tokoh publik, influencer, hingga brand lokal kini harus berhati-hati karena komentar yang dinilai salah bisa langsung viral dan diserang oleh netizen.
Contoh: Kasus-kasus komentar artis tentang isu sensitif seperti agama, gender, atau politik bisa langsung berujung trending dan boikot. Namun, ada juga kasus di mana netizen cepat “memaafkan” setelah klarifikasi.
Dampak Cancel Culture: Dua Sisi Mata Uang
💡 Positif:
-
Mendorong akuntabilitas sosial.
-
Memberikan suara pada kelompok yang selama ini terpinggirkan.
-
Mengangkat isu-isu penting seperti rasisme, seksisme, atau pelecehan.
⚠️ Negatif:
-
Tidak memberi ruang untuk rehabilitasi atau pertobatan.
-
Bisa menjadi persekusi online dan menyebabkan dampak psikologis.
-
Tidak selalu berdasarkan informasi yang akurat, sehingga memicu trial by social media.
Apakah Cancel Culture Bisa Diseimbangkan?
Muncul gagasan bahwa cancel culture perlu digantikan dengan pendekatan “accountability culture” — yakni, bukan hanya menghukum, tetapi mendorong pertanggungjawaban, pemulihan, dan edukasi.
Beberapa tokoh seperti Trevor Noah dan Barack Obama menyuarakan bahwa “memanggil” (call out) lebih baik daripada “membatalkan” jika ingin membangun masyarakat yang lebih adil dan sadar.
Kesimpulan: Dunia di Persimpangan Digital
BACA JUGA: Viral dalam Hitungan Jam: Mekanisme Penyebaran Cancel Culture di Platform Digital
Cancel culture menunjukkan betapa kuatnya suara publik di era digital. Dunia kini berada di persimpangan: antara mendukung keadilan sosial dan menjaga ruang dialog yang sehat. Cara tiap budaya menangani pembatalan mencerminkan nilai-nilai dan sensitivitas sosial masing-masing.
Yang pasti, dunia maya kini bukan sekadar tempat berbagi, tapi juga ruang pengadilan sosial yang nyata. Dan kita semua — netizen global — adalah juri sekaligus peserta dalam drama besar bernama cancel culture.